FSPKEP.id – Pendidikan adalah jantung pembangunan bangsa. Ia menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, bermoral, dan berdaya saing tinggi. Namun, realitas pendidikan di Indonesia kerap kali jauh dari ideal. Salah satu luka paling menganga dalam sistem pendidikan kita saat ini adalah masalah sistem domisili dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan yang awalnya ditujukan untuk menciptakan pemerataan akses justru menjadi sumber ketidakadilan, korupsi kecil-kecilan, dan runtuhnya nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat.
Sistem zonasi atau domisili mulai diterapkan dalam PPDB sejak beberapa tahun lalu dengan maksud yang tampaknya mulia: agar semua anak Indonesia, terutama dari kalangan tidak mampu, mendapat kesempatan sekolah yang setara, tanpa harus bersaing berdasarkan nilai semata. Tapi, apa yang terjadi kemudian adalah ironi besar. Niat baik itu justru membuka celah manipulasi besar-besaran.
Kini, banyak orang tua “terpaksa” memalsukan domisili demi menyekolahkan anak mereka di sekolah favorit—bukan karena ambisi semata, melainkan karena mereka sadar bahwa kualitas pendidikan masih sangat timpang antar wilayah. Sekolah unggulan tetap menjadi primadona karena mutu guru, fasilitas, dan budaya belajar yang jauh lebih baik. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa menyalahkan orang tua yang ingin masa depan terbaik untuk anak-anak mereka?
Masalahnya bukan hanya pada tindakan pemalsuan itu sendiri, tetapi pada sistem yang menciptakan kebutuhan untuk berbohong. Di berbagai daerah, praktik ini sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang tua rela menyewa rumah palsu, meminjam alamat kerabat, hingga “membeli” surat keterangan domisili dari oknum-oknum tertentu—semuanya demi satu tujuan: mengakali sistem.
Lebih tragis lagi, tindakan ini bahkan melibatkan aparat pemerintah. Ada yang membisniskan pengurusan surat pindah domisili fiktif. Ada yang dengan mudah memberikan keterangan palsu demi imbalan uang. Dalam hal ini, pendidikan yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran moral justru membuka ruang bagi praktik-praktik tidak etis bahkan sejak dari proses pendaftarannya.
Sementara itu, anak-anak yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah namun berasal dari latar belakang ekonomi rendah harus kalah saing dengan “pendatang fiktif” yang lebih mampu secara finansial untuk memanipulasi sistem. Di sini kita melihat dengan gamblang bagaimana sistem ini menciptakan diskriminasi baru, memperparah kesenjangan, dan justru mengerdilkan esensi dari keadilan pendidikan.
Alih-alih menuntaskan ketimpangan, sistem domisili justru menjadi simbol dari kegagalan pemerintah dalam meratakan kualitas pendidikan. Jika setiap sekolah di Indonesia memiliki mutu yang setara, tentu orang tua tidak akan mati-matian ingin masuk ke sekolah tertentu. Tapi kenyataannya, sistem pendidikan kita masih berpijak pada kasta-kasta terselubung—di mana hanya sekolah tertentu yang dianggap “layak”, sementara yang lain sekadar pelengkap penderitaan.
Kita harus berani mengakui bahwa akar masalah bukan hanya terletak pada perilaku masyarakat, tetapi pada kebijakan yang setengah matang, tidak adaptif, dan enggan melihat realitas sosial. Pendidikan tidak bisa dipaksa untuk setara secara geografis, jika infrastrukturnya sendiri belum setara. Pemerintah harusnya lebih fokus membenahi kualitas di setiap sekolah, bukan sekadar mendistribusikan murid berdasarkan alamat.
Bobroknya sistem domisili dalam pendidikan Indonesia adalah cermin kegagalan moral, struktural, dan kebijakan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal bagaimana kita menciptakan masa depan bangsa. Jika sejak awal anak-anak diajarkan bahwa untuk mendapat pendidikan yang baik mereka harus berbohong, memalsukan data, dan bersaing dengan cara licik, maka apa yang bisa kita harapkan dari masa depan mereka?
Kini saatnya kita bersuara. Menuntut keadilan bukan hanya dalam bentuk angka-angka anggaran, tapi dalam bentuk sistem yang jujur, manusiawi, dan benar-benar berpihak pada anak-anak Indonesia—tanpa melihat alamat mereka. Alf


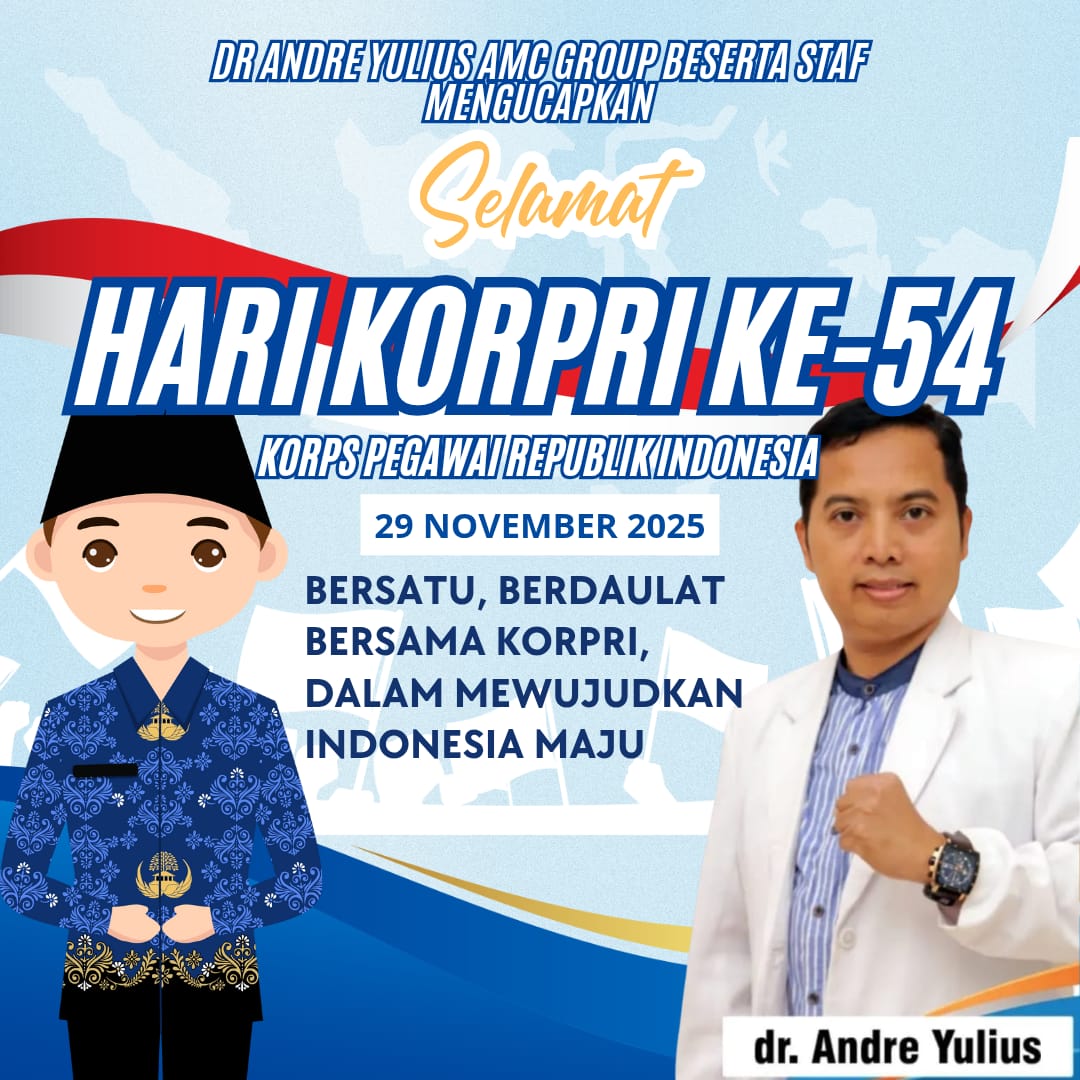




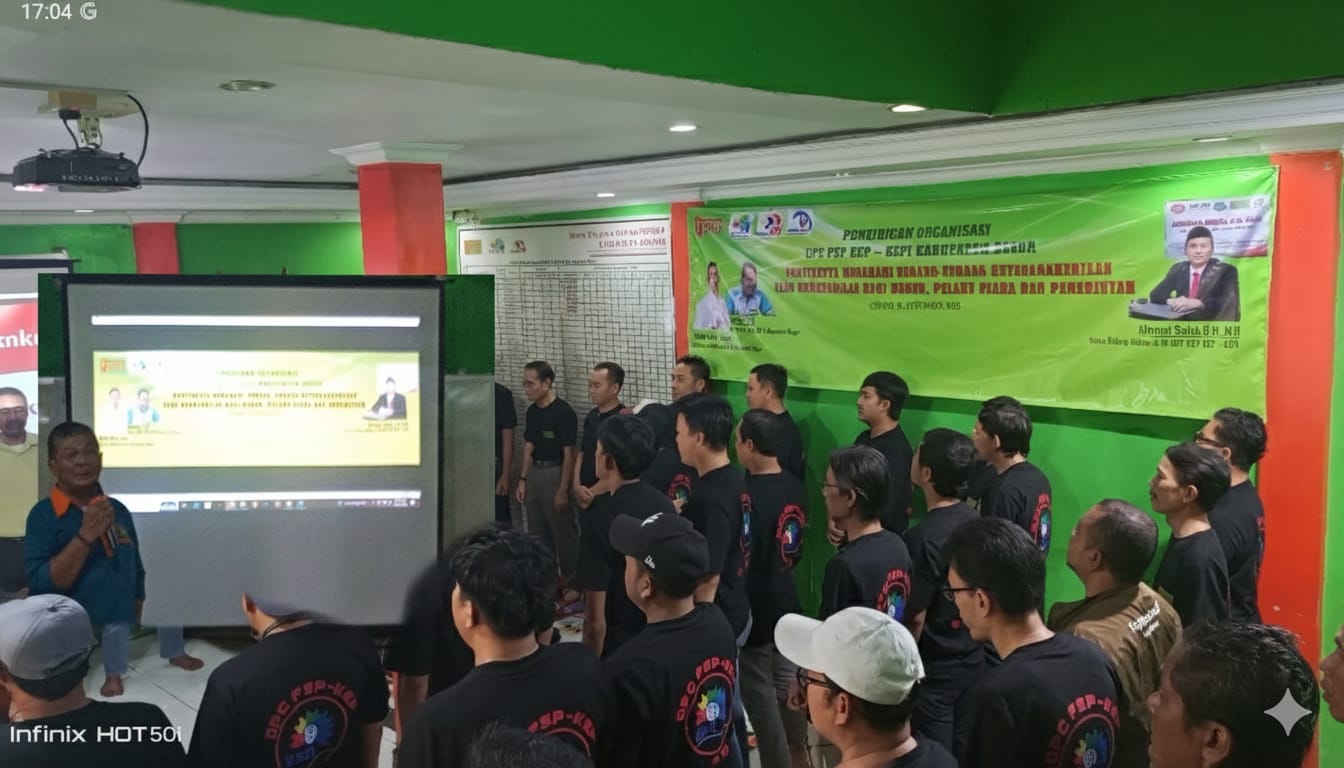



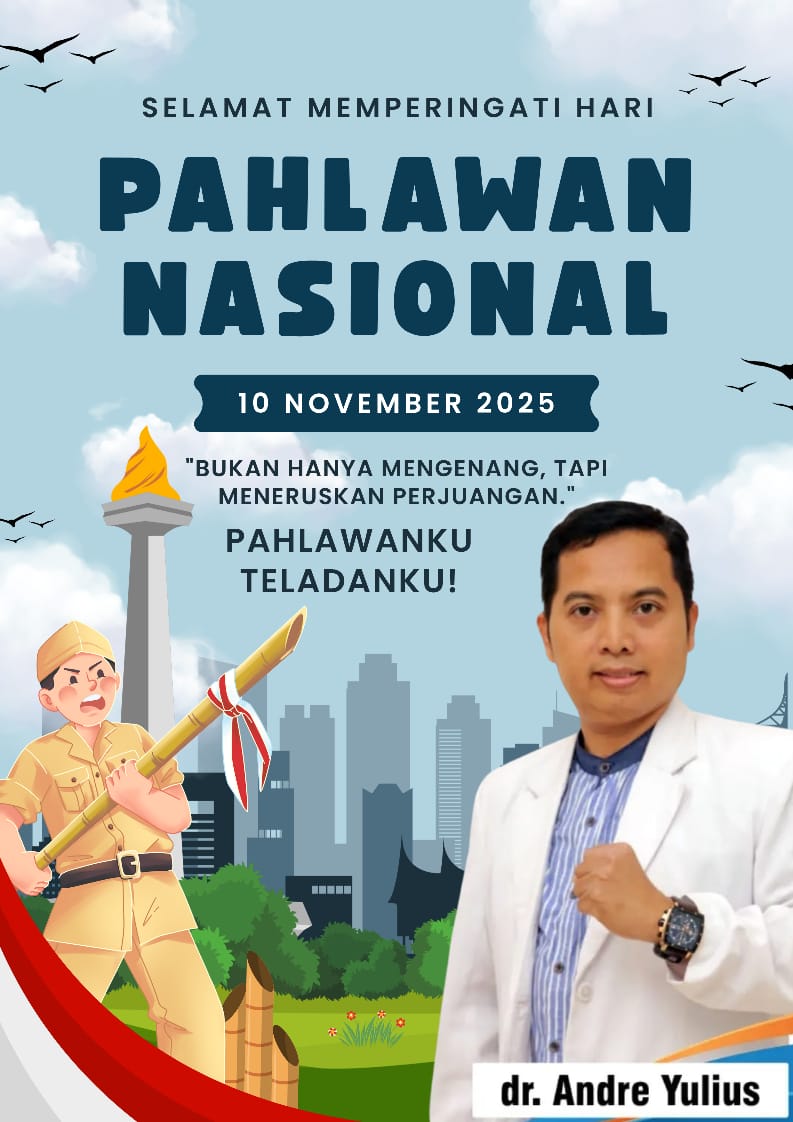














Leave a Reply