Oleh : Tubagus Wahyudi | Tim Media FSPKEP Indonesia
Jakarta, fspkep.id | Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu pilar utama hubungan industrial yang sehat, adil, dan demokratis. Dalam konsep ideal, PKB lahir dari proses perundingan yang setara antara pekerja yang diwakili serikat, dan pengusaha sebagai pemberi kerja. Ia bukan sekadar kontrak kerja, melainkan refleksi dari keseimbangan kekuasaan, perlindungan hak, dan arah hubungan jangka panjang. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia belum menikmati manfaat dari keberadaan PKB. PKB justru lebih banyak hadir sebagai dokumen simbolik tanpa daya paksa, dan cenderung hanya dinikmati oleh kalangan pekerja di sektor formal dan perusahaan besar.
Data Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2024 menunjukkan bahwa dari sekitar 265.000 perusahaan formal yang terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 15.906 perusahaan (sekitar 6%) yang memiliki PKB aktif dan tercatat secara resmi di sistem pelaporan nasional. Angka ini sangat memprihatinkan mengingat jumlah pekerja yang bergantung pada perjanjian kerja perorangan jauh lebih banyak. Bahkan, sebagian besar pekerja di sektor padat karya, industri kecil-menengah, jasa ritel, dan sektor informal tidak memiliki akses ke perundingan kolektif sama sekali. Ini menandakan bahwa mekanisme hubungan industrial di Indonesia masih sangat timpang dan eksklusif.
Fenomena ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam. Banyak perusahaan di Indonesia khususnya yang tidak memiliki serikat pekerja internal lebih memilih membuat peraturan perusahaan secara sepihak ketimbang merundingkan PKB. Akibatnya, pekerja berada dalam posisi lemah, tidak hanya dalam hal upah dan jaminan kerja, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan kerja mereka sehari-hari. Budaya feodal di banyak tempat kerja, dengan dominasi penuh manajemen terhadap kebijakan ketenagakerjaan, memperparah situasi ini. Proses perundingan, bila pun dilakukan, seringkali hanya formalitas tanpa esensi demokratis, karena pekerja tidak dibekali pemahaman hukum, dan serikat lemah atau dikendalikan oleh perusahaan (yellow union).
Lebih jauh, peran negara dalam mendorong PKB sebagai norma hubungan industrial juga masih minim. Meski Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi sistem e-PP dan e-PKB sejak 2020 sebagai upaya digitalisasi dan transparansi, sistem ini belum cukup kuat mendorong pengusaha untuk menyusun PKB secara sukarela dan progresif. Belum ada kebijakan yang mengatur mandatory collective bargaining (perundingan wajib) bagi perusahaan dengan jumlah pekerja tertentu. Bahkan, pelatihan tata cara penyusunan PKB yang diselenggarakan pemerintah pusat masih sangat terbatas. Triwulan II tahun 2024, misalnya, hanya sekitar 160 pekerja di seluruh Indonesia yang dilaporkan mengikuti pelatihan PKB (data.kemnaker.go.id). Angka ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan peningkatan kapasitas serikat secara nasional.
Di sisi lain, masih terjadi ketimpangan geografis dan sektoral dalam penyusunan PKB. Kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Timur relatif lebih aktif menyusun PKB, sementara daerah-daerah luar Jawa, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM, hampir tidak tersentuh. Serikat pekerja di daerah juga banyak yang belum memiliki akses konsultasi hukum atau pendampingan profesional, sehingga isi PKB kerap tidak mencerminkan kepentingan pekerja secara utuh mulai dari tidak dicantumkannya jaminan sosial tambahan, sistem sanksi yang berat sebelah, hingga masa kerja kontrak yang terus diperpanjang tanpa kepastian hubungan kerja tetap.
Meskipun demikian, terdapat titik terang dari beberapa sektor industri progresif, seperti teknologi dan jasa digital. Beberapa perusahaan multinasional mulai mencantumkan klausul PKB yang menyentuh kebutuhan kontemporer pekerja, seperti hak kerja jarak jauh (remote working), cuti untuk kesehatan mental, tunjangan keseimbangan kerja-hidup, dan transparansi sistem evaluasi kinerja. Tetapi praktik ini masih sangat terbatas dan bersifat insidental, tidak menjadi norma industri nasional.
Melihat realitas ini, Indonesia membutuhkan terobosan kebijakan yang tegas dan sistemik. Pemerintah harus segera mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja untuk menyusun PKB sebagai bagian dari pemenuhan standar ketenagakerjaan. Selain itu, diperlukan insentif fiskal bagi perusahaan yang menyusun PKB progresif serta peningkatan anggaran pendidikan dan pendampingan serikat pekerja di daerah. Terpenting, inspektorat ketenagakerjaan harus diperkuat, tidak hanya dalam jumlah petugas, tetapi juga dalam kewenangan menilai substansi dan implementasi PKB.
Jika tidak ada langkah tegas, PKB hanya akan menjadi simbol legalitas tanpa makna substantif. Ia akan terus tertahan sebagai dokumen administratif yang mengisi rak di Kementerian, sementara jutaan pekerja terus bekerja tanpa perlindungan kolektif. Di tengah impitan ekonomi dan ketidakpastian global, pekerja Indonesia layak mendapatkan lebih dari sekadar janji formal. Mereka membutuhkan instrumen perlindungan yang nyata, adil, dan berpihak dan PKB seharusnya menjadi salah satunya., dan sektor informal tidak memiliki akses terhadap negosiasi kolektif yang layak. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya posisi tawar serikat pekerja lokal, terbatasnya pendidikan hukum ketenagakerjaan, dan masih kuatnya budaya “perintah dari atasan” yang melemahkan demokrasi di tempat kerja. Akibatnya, banyak PKB disusun secara sepihak, dengan klausul yang justru lebih menguntungkan pengusaha.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan dari pemerintah. Meski ada upaya digitalisasi melalui portal PKB online di situs Kemnaker, sistem pelaporan dan evaluasi masih bersifat pasif dan belum mampu memastikan kepatuhan perusahaan secara menyeluruh. Bahkan dalam banyak kasus, PKB hanya menjadi dokumen formalitas tanpa implementasi yang nyata di lapangan. Beberapa provinsi memang telah merumuskan panduan penyusunan PKB sektoral, namun masih sebatas imbauan, bukan regulasi yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara dalam memastikan keadilan industrial belum maksimal.
Namun di balik tantangan tersebut, muncul harapan dari beberapa perusahaan yang mulai menyusun PKB dengan memasukkan klausul progresif seperti fleksibilitas jam kerja, tunjangan internet untuk kerja jarak jauh, serta cuti untuk kesehatan mental. Sayangnya, praktik ini masih sangat terbatas dan belum menjadi standar industri secara luas. Untuk menjawab persoalan ini, perlu ada terobosan kebijakan, seperti mewajibkan perusahaan dengan jumlah pekerja tertentu untuk memiliki PKB, memberikan subsidi pelatihan negosiasi untuk serikat pekerja, serta memperkuat inspektorat ketenagakerjaan yang mampu menindak tegas pelanggaran implementasi PKB.
Dengan perbaikan sistemik tersebut, PKB dapat berkembang menjadi alat penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja. Sebaliknya, jika dibiarkan seperti sekarang, PKB hanya akan menjadi simbol kosong dari cita-cita kesejahteraan pekerja yang tak kunjung terwujud.










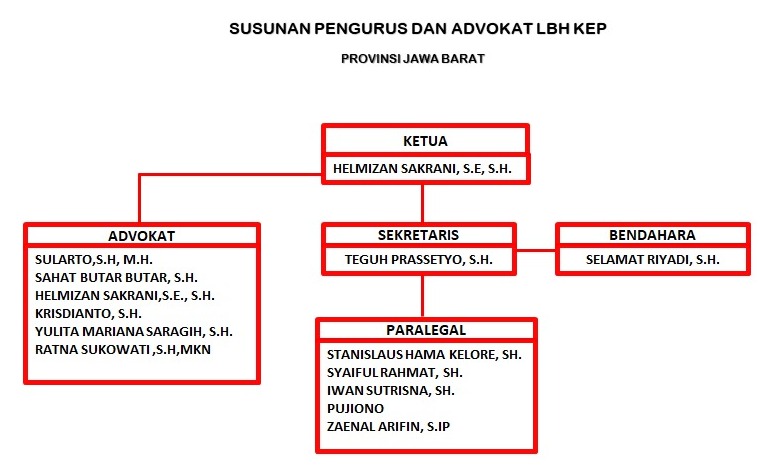











Leave a Reply